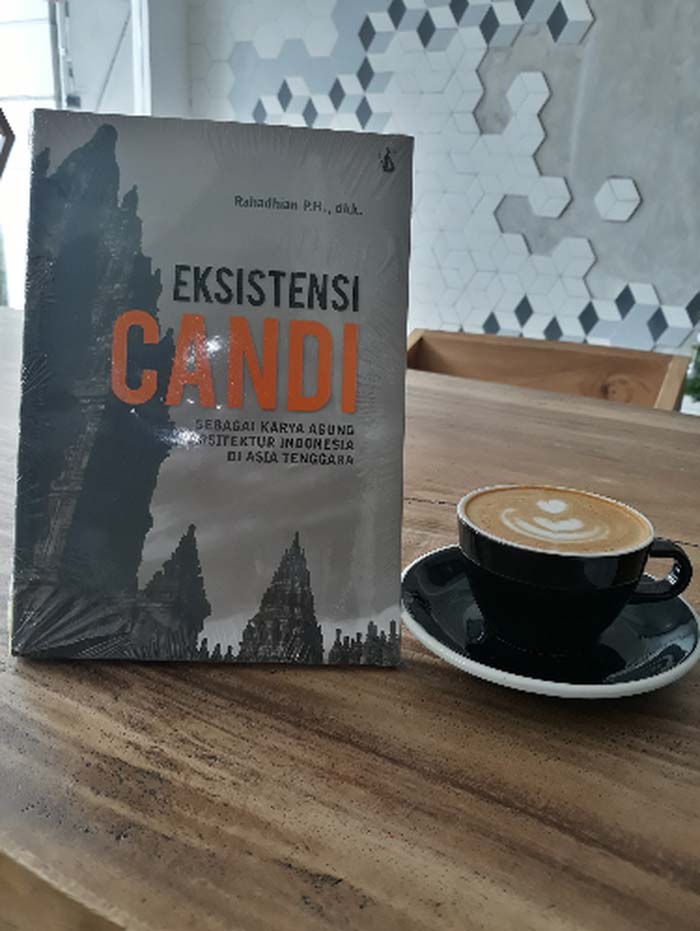
Judul Buku: Eksistensi Candi Sebagai Karya Agung Arsitektur Indonesia di Asia Tenggara; Penulis: Rahadhian P. H., dkk; Penerbit: Kanisius, 2018; Tebal: 256 halaman
Setiap kali berkunjung ke candi, memang selalu meninggalkan kekaguman bagi pengunjung. Akan ada sejumlah pertanyaan yang terlintas dalam benak mereka, misalnya bagaimana dulu nenek moyang kita membangunnya? Mengingat teknologi masa itu belumlah secanggih masa ini.
Candi merupakan bagian dari peninggalan sejarah masa klasik atau Hindu-Budha di Indonesia. Pengertian candi menurut Permana (2016:76) adalah istilah umum untuk menamakan semua bangunan peninggalan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia, baik berupa pemandian kuna, gapura, atau gerbang kuna, maupun bangunan suci keagamaan. Bahkan di beberapa tempat di Jawa Timur dan Jawa Tengah, suatu kelompok arca yang menjadi pundhen desa seringkali disebut candi.
Candi-candi tersebut tersebar di wilayah Indonesia, baik di Sumatra maupun di Pulau Jawa. Kita mengenal adanya Candi Borobudur, Sewu, Gedong Songo, Dieng di Jawa Tengah, Candi Sambisari, Prambanan, Kedulan ada di DI Yogyakarta. Sementara di Jawa Timur ada Candi Penataran, Singosari, Kidal. Di Jawa Barat juga terdapat kompleks percandian Batujaya.
Arsitektur candi menjadi topik pembahasan buku ini. Penelitian pada warisan bangunan masa lalu di Indonesia selama ini kerap kali hanya dari tinjauan arkeologis. Pada dasarnya candi adalah bangunan sehingga semestinya juga menjadi bagian penting dari pengkajian yang bersumber pada ilmu arsitektur. Pendekatan arsitektural menjadikan candi tidak dianggap sebagai benda yang statis (pathological monument) saja. Candi juga bisa berlaku dinamis (propelling monument), baik dalam wujud bendanya sendiri maupun wujud transformasinya gagasan arsitekturalnya.
Candi dapat dikenali sebagai wujud keunggulan tradisi arsitektur Indonesia. Keunggulan tersebut baik dalam kedinamisan, variasi bentuk, maupun pengaruhnya pascamasa Hindu-Budha. Arsitektur candi di Indonesia menunjukkan hasil local genius khas yang dimiliki Indonesia. Candi di Indonesia berbeda dengan kuil-kuil yang ada di India, meskipun tradisi Hindu-Buddha berasal dari sana.
Penelitian ini mencoba menunjukkan bahwa keunggulan tradisi arsitektur (candi) Indonesia telah memberi pengaruh kuat sampai ke mancanegara, khususnya Asia Tenggara. Kehadiran buku ini bisa menjadi jawabannya. Buku ini menampilkan sisi menarik yang sederhana yakni melakukan perbandingan dengan menjejerkan beberapa candi yang menjadi objek penelitian, yaitu Candi di Indonesia dan Kamboja.
Candi yang menjadi objek penelitian ini berasal dari masa klasik Kerajaan Mataram Kuna yaitu Candi Prambanan, Candi Borobudur, dan Candi Sewu di Indonesia. Candi-candi ini didirikan sekitar abad ke-8 sampai 9 Masehi. Sementara di Kamboja ada Candi Candi Bakong, Preah Ko (mewakili masa transisi 825-893 Masehi), Angkor Wat (mewakili masa kejayaan masa Angkor 1113-1177 Masehi), dan Bayon (mewakili masa Angkor akhir atau 1181 hingga abad ke-13 Masehi).
Cara kerja metode ini adalah dengan menyoroti secara detail sejumlah bagian candi melalui tipomorfologi arsitekturnya. Tipomorfologi adalah pendekatan untuk mengungkapkan struktur fisik dan keruangan dan merupakan gabungan dari studi morfologi dan tipologi. Hal-hal yang dikaji meliputi denah, sosok, perletakan, elemen fisik dan lain-lain.
Hasilnya memang luar biasa. Metode ini mampu memberikan hipotesis baru yang didukung bukti konkrit dari kesamaan maupun perbedaan dari candi-candi tersebut. Bahwa candi-candi di Indonesia yang berasal dari masa klasik tersebut ternyata mampu menginspirasi berdirinya candi-candi di Kamboja.
Tetapi pada candi-candi di Kamboja juga dijumpai perbedaan dengan candi-candi Indonesia. Ada sejumlah kemungkinan yang disampaikan peneliti terkait hal itu. Pertama, adanya perbedaan material dan teknologi yang menyulitkan candi masa transisi di Kamboja untuk membuat atau mempertahankan bentuk-bentuk yang sama seperti di Jawa.
Kedua, ada kemungkinan bahwa masyarakat Kamboja memiliki pemahaman dan nilai-nilai Hindu yang berbeda. Hal ini membawa konsekuensi pada hilangnya sejumlah ornamen di candi Kamboja. Ketiga, masyarakat Kamboja juga memiliki local genius, sehingga mereka tidak serta merta meniru candi di Jawa. Kemungkinan, mereka sengaja membuat perubahan-perubahan pada unsur arsitektur candi sesuai dengan tradisi lokal.
Misalnya keberadaan ornamen ular naga berkepala banyak (lima/tujuh/sembilan) merupakan ornamen khas arsitektur Kamboja. Pada Candi Bayon, banyak terlihat ornamen ular naga berkepala tujuh. Pada pedimen pintu Bayon, naga berkepala tujuh muncul dari dalam mulut makara. Sementara ornamen tersebut tidak dijumpai di Candi Prambanan, Borobudur, dan Sewu.
Buku ini juga memastikan bahwa Candi Induk Prambanan menjadi gedung tertinggi pertama di Asia yang hadir sebelum abad ke-10. Candi Induk Prambanan memiliki ketinggian 47 meter atau setara dengan gedung 10 lantai.
Candi Induk Prambanan, meskipun berbeda tingginya dengan Angkor, dibangun tidak dengan kaki yang tinggi, namun memang dibangun dengan sosok yang tinggi dan besar dari bawah ke atas. Ketinggiannya setara dengan gabungan kaki Angkor yang berundak dan candi utamanya. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi kontruksi high rise building candi Jawa lebih unggul dan maju.
Tradisi membangun bangunan tinggi di Kamboja baru dimulai sekitar 50-100 tahun sesudah berdirinya Candi Prambanan. Angkor Wat sendiri baru didirikan pada awal abad ke-12. Teknologi konstruksi bangunan tinggi di Nusantara pada abad ke-9 telah menunjukkan perkembangan inovasi yang signifikan. Perkembangan ini yang digunakan oleh candi-candi di Kamboja.
Penelitian ini menjadi penelitian rintisan yang menarik bagi perkembangan pengaruh arsitektur Indonesia di Asia Tenggara. Selama ini arsitektur candi di Indonesia terkesan dikesampingkan pembahasannya. Padahal arsitektur candi ini merupakan perwujudan kebudayaan pada masanya. Dan mampu menginspirasi kebudayaan yang serupa di tingkat regional Asia Tenggara.
Shinta Dwi Prasasti staf Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta, sedang menempuh S2 Arkeologi di Prodi S2 Arkeologi FIB UGM